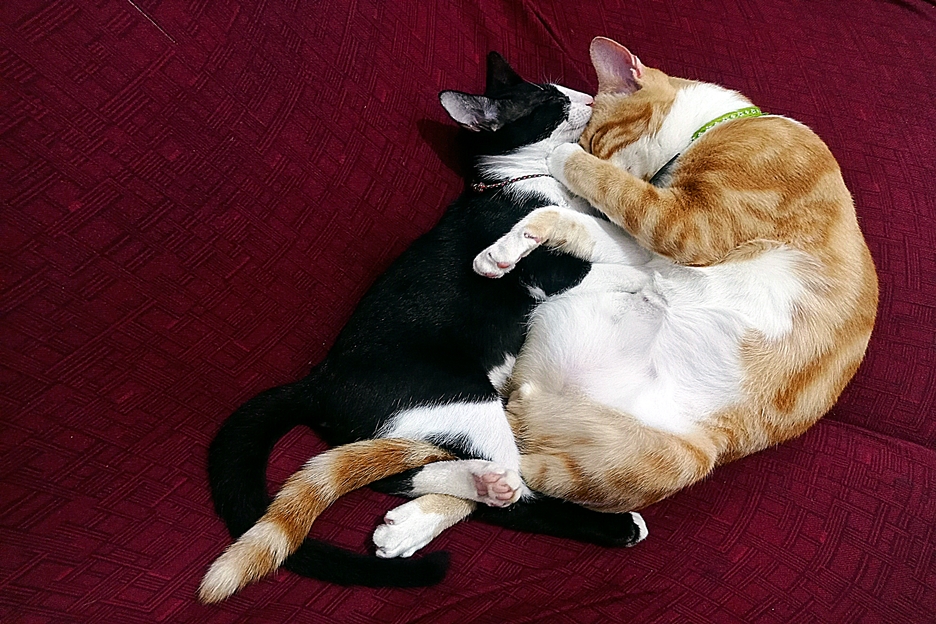
“Jangan ngarang,” bisik Jamal pagi-pagi.
“Siapa yang ngarang!” pekikku garang.
“Lha itu, mimpi dicium segala,” ulas Jamal tenang-tenang.
“Memang benar kok,” timpalku sewot.
Tiba-tiba aku merasa diremehkan suamiku hanya karena aku berterus-terang menceritakan mimpiku semalam. Sungguh, aku tidak sedang memikirkan pujangga legendaris itu, apalagi sedang membaca karya-karyanya. Aku sudah lama tak membaca buku apalagi novel sejenis itu. Kecuali bertahun-tahun lalu ketika karya-karya pengarang kaliber dunia itu menjadi semacam kitab suci bagi mahasiswa pencari makna di negeri bernama Indonesia.
Baca juga: Kegagapan Manusia Perbatasan
Benar, karya-karyanya menjadi bacaan wajib mahasiswa era 1990-an. Diam-diam tersebar dari balik meja kuliah, ke meja lain. Buku roman sejarahnya terbaru, menjadi sebuah peta besar bagi kami mahasiswa Fakultas Hukum demi membantu kami mencerna hakikat tatanegara sejelas-jelasnya. Justru, karya sastra yang menjadi referensi sahih bagi kami. Ia lebih masuk akal dari karya ilmiah manapun. Kami tahu sama tahu belaka dan seperti bisa mengendus aroma manusia yang berseberangan dengan keyakinan kami ini.
Secermat mungkin kami menghindarkan buku yang kami baca secara bergiliran dari orang-orang yang berseberangan. Bahkan mengenai sang buku, sudah tak jelas lagi siapa gerangan pemilik buku dan dari mana buku itu berasal. Kami tak peduli kecuali lekas-lekas menelusuri isinya. Rahasia kami junjung tinggi. Betapa berdebar ketika membacanya dan lega ketika mengusaikannya. Bukan hanya soal alur cerita yang tak goyah mengendap di kepala tapi pesan-isi cerita seperti peta-buta yang harus kami kuak sebagai petunjuk hidup: mengurai kemacetan hidup di negeri ini.
Hanya dengan isyarat tatapan mata –bagi sesama yang telah membaca– kami seperti merasa saling dekat dan kenal lama bahkan jauh sebelum kami lahir ke dunia. Yah, seperti halusinasi tapi ini terjadi hanya karena sama-sama membaca karya penulis kawakan ini. Betapa pengaruh karyanya menjadi nafas gelora dan semangat kami ketika itu. Mungkin, itu disebut sebagai lahirnya idealisme.
Memang sih, sebagian dari kami sekedar ikut-ikutan. Jarang yang memang karena rasa ingin tahu. Lebih sedikit lagi yang melakukan sesuatu untuk mewujudkan keterpanggilan tanpa syarat melawan segala sesuatu yang kian hari kian tak memihak kepentingan rakyat dalam makna terdasar. Negeri ini macet!
Baca juga: Penyair dan Penyu Air
Dan mimpi dicium pujangga gaek? Atau mencium? Mengapa hari ini? Di saat aku sudah tak lagi memikirkan apa dan bagaimana sebaiknya negara yang kutinggali ini mencapai tujuannya. Aku telah habis-habisan membunuh pikiranku dicaplok realita yang menganga dan menciptakan kesibukan yang tiada sudah. Toh kehidupan mahasiswa yang penuh gelora sudah lama kutinggalkan. Sekedar masa lalu yang sangat jauh dari kehidupanku hari ini. Romantisme, tidak lebih.
Aku tak pernah berkenalan dengan pujangga yang itu. Aku juga tidak tergila-gila dengan karyanya. Apalagi secara pribadi sebagaimana umumnya pengarang, seniman dan sejenisnya, tentu ia manusia yang keras kepala lagi berjiwa merdeka kelewatan. Tak sudi memikirkan tetek-bengek sehari-hari. Tidak rapi. Playboy. Mau menang sendiri. Pendebat Tuhan. Moralitasnya nol koma nol. Egois! Dadaku berdegup tiba-tiba merasa berhak untuk mencaci-maki manusia yang tiba-tiba nongol dalam mimpiku. Seolah-olah aku telah mengenalnya lama. Apa urusan dia denganku? Apakah aku pernah berhutang padanya? Ia kepadaku? Apalagi! Tidak, tidak, tidak!
Aku gelisah.
Aku ini, jangankan memikirkan bagaimana Indonesia bernafas: sebuah negara yang tak nampak wujudnya. Sedang menghidupi apa-saja yang mewujud saat ini kian hari kian rumit. Siapa yang tak tahu resesi dunia? Perusahaan-perusahan besar skala dunia yang secara akali tak akan gulung tikarpun akhirnya bertekuk-lutut pada kepanikan pasar. Aku bekerja, menerima gaji tiap awal bulan, seperti numpang lewat permisi dan setelah itu aku harus bersegera bekerja mencari uang atau mungkin demi eksistensi. Uang dan eksistensi. Mungkin inilah zaman kolobendu yang disebut-sebut orang dulu. Zaman serba absurd dan aku mulai gelisah dengan mimpi yang masih terngiang di kepala hingga terjaga. Ada apa gerangan?
“Dicium sang pujangga ndak apa-apa, apapun maknanya. Tapi mencium beliau tidak bagus sebab istri beliau pasti tidak setuju. Jika sang istri tidak cemburu berarti segala cium boleh berbahagia. Hiduplah Indonesia Raya!” tutur Jamal sambil menari-nari keluar dari kamar mandi.
Aku menghindari tatapan Jamal. Tak kutanggapi goda-rayu-lucunya saat mengawali hari yang biasanya kunikmati. Amat kunikmati.
Aku berpikir.
Jadi aku yang mencium atau dicium? Tanyaku di dalam hati merasa hidupku selama ini kering-kerontang. Apa ada yang keliru dengan kehidupan perkawinan kami? Jamal berupaya mewarnai hidupku dengan corak paling menggairahkan. Itu aku tahu. Roti tawar kuoles butter orchid lekas-lekas, lalu mengaduk kopi untuk Jamal keras-keras.
“My love, kalau sedang tidak enak hati, lebih baik aku bikin kopi sendiri. Tak apa-apa. Aku bisa melakukannya,” bisik Jamal tepat di telinga kananku.
Aku terperanjat dan menyerah tanpa syarat, “maaf …”
Tangan kanan Jamal meraih sendok dari tanganku dan tangan kirinya melingkar di pinggangku, tidak longgar tapi juga tidak terlalu ketat. Sebuah pelukan yang membuat nyaman. Sesaat. Hanya sesaat.
Baca juga: Soesilo Toer, Ziarah Literasi
Aku kemudian duduk tanpa menjelaskan apapun. Aku tak banyak bicara sebagaimana biasa. Jamal juga tak mencoba mengomentari dan apalagi lekas-lekas menuntut ketidakbiasaan ini. Ia mencoba meladeniku dengan menyediakan apa yang biasa kulahap sebelum berangkat ke kantor.
“Boleh aku tidak makan, pagi ini?” rajukku merasa mual. Sangat mual.
Jamal mengeryit. Ia tak berkata apa-apa tapi terang-benderang menunjukkan keberatan. Tak rasional. Oke, kali ini aku terlalu mendramatisir apa yang sewajarnya orang bisa segera melupakan mimpi semalam. Baik Jamal, aku akan berpikir ala caramu berpikir: lugas.
Istrinya cemburu? Atau kau yang mulai terserang cemburu? Jamal? Hanya karena aku bermimpi mencium sang pujangga? Atau dicium pak tua tapi gaya? Sebuah ciuman di pipi kanan belaka. Tak ada istimewanya. Batinku serta-merta membela diri sambil menatap lekat suamiku. Kini Jamal yang menghindari tatapan mataku.
Lekas! Lekas! Lekas!
Kata-kata magis yang harus kami bisikkan di dalam hati pagi-pagi. Lima menit saja terlambat keluar dari halaman rumah artinya sepanjang perjalanan menuju kantor akan menjumpai perbedaan yang nyata. Akibatnya kami akan menjumpai hal-hal yang tak sama pula. Kami kurang suka pada hal-hal yang tak akrab, tak sama, apalagi yang tak pernah kami alami sebelumnya.
Jamal mencium pipiku sambil lalu, bukan bibir.
“Ada apa Sayang?” tanyaku.
Jamal mengeryit lagi, “seharusnya saya yang mengajukan pertanyaan itu,”.
Jamal mulai ber-saya. Kiranya tatapan mataku kian menghujam ke dalam mata suamiku. Tatapan matanya mengambar. Aku mendapati sorot mata sedih yang beberapa menit lalu masih menyampaikan pesan melucu. Apakah mataku mengirim pesan yang salah? Mata lelakiku lekas sekali memantulkan cahaya pesan luka.
“Tak mau bilang apa-apa, Sayang?” tandasku.
Jamal geming, menutup pintu mobil. Berlalu.
Pekerjaan kantor hari itu kuselesaikan dengan enersi serupa dengan hari-hari lalu. Istirahat siang kusempatkan pergi ke toko buku. Tak sulit menemukan buku-buku karya sang pujangga kita itu sekarang. Kuborong beberapa judul, termasuk empat jilid bukunya yang legendaris itu. Sesampai di meja kerja, tak kupedulikan pandangan ganjil kawan-kawan kantor. Beberapa menyampaikan pendapat lewat isyarat mata: kurang kerjaan. Selebihnya tak ambil pusing setelah beberapa saat menatap tentenganku.
Jamal datang pukul satu dini hari!
Aku membaui hawa alkohol di mulutnya saat ia menyampaikan sebuah ciuman di kening. Di kening.
Aku sampai di bagian 11 buku jilid pertama pujangga wagu itu:
Teringat aku pada berita-berita koran yang memashurkan obat pelenyap pening paling mujarab dalam sejarah ummat manusia. Katanya Jerman yang menemukan, dinamai: Aspirin. Tapi obat itu baru berupa berita. Di Hindia belum lagi kelihatan, atau aku yang tidak tahu. Uh, Hindia, negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa! (*)
Setelah sibuk sendiri di toilet, Jamal tak mengenakan piyama yang kusiapkan untuknya. Jamal langsung tidur tengkurap dengan kaos robek di ketiak kesukaannya. Ia tahu aku kesal dengan kaos yang satu itu. Tanpa sembayang, tanpa memandang padaku. Jadi kalau sedang tidak enak hati padaku, Tuhan pun kena getahnya. Great. Jadilah bocah! Semaumu!
Aku meneruskan bacaanku.
Sungguh, aku tak bisa menangkap apapun dari apa yang sedang kubaca.
“Sayang, kita harus bicara,” kataku pada suamiku tak berapa lama.
“Besok pagi saja. Saya lelah,” tanggap Jamal.
Kutepuk-tepuk punggungnya. Jamal masih ber-saya. Kata-kata tak mempan, kemudian punggungnya pun kupijit. Jamal menjauhkan punggungnya. Akupun tak menunggu penolakan lain. Selekasnya aku beranjak dari peraduan dengan dada terasa berlubang. Aku meneruskan bacaan hingga dini hari menjelang.
Baca juga: Mengapa Kita Harus Menulis?
Pembicaraan besok pagi saja itu tiada. Tidak pagi berikutnya dan tidak pagi berikutnya lagi hingga hampir 10 hari lenyap dari penanggalan. Aku nyaris tak kuat untuk tidak meledakkan tangis. Tatapan mataku kian liar tak bisa kututupi. Tatapan menelanjangi. Jamal kian rajin menyembunyikan sinar matanya.
Apa hanya karena sebuah ciuman di dalam mimpi, nasib perkawinan kami menjadi genting begini? Di mana letak logika? Cinta boleh jadi serupa misteri tapi proses cinta itu sendiri adalah bagian dari hukum kausalitas yang sangat bisa dirunut dan dipertanggungjawabkan sebab-akibatnya.
“Aku minta maaf. Tolong maafkan aku, Sayang,”.
Kupinggirkan harga diri wanita dihadapan laki-lakiku. Kupeluk punggung suamiku. Kali ini aku berjanji tak akan melepaskan pelukanku sampai ia mau memaafkanku.
Kami pun duduk berhadap-hadapan di depan meja makan. Kami lupakan berapa lama waktu telah berlalu. Tiada yang mampu membuat kami lekas-lekas pagi ini. Kami ingin sudahi ketidakenakan ini. Sudah terlalu dingin bagi hati kami masing-masing. Jamal menyampaikan pengakuan bahwa ia takut. Awalnya soal mimpi mendapat ciuman dari pujangga yang orangnya pun sudah tidak ada, kemudian sorot mata yang ia belum pernah kenal di mataku. Kemudian aku lebih asyik membaca katimbang merengek-rengek minta diantar ke salon.
Aku memeluk suamiku. Aku tak ingin terlambat menyadari ini. Sebongkah hati seorang lelaki terbungkus tubuh yang penuh dan bahasa jiwanya mengamankan hatiku, ternyata amat halus-peka. Terlalu peka. Mimpi, tatapan mata, dan buku bisa menjadi pemicu sembilan puluh sembilan alasan bagi suamiku tak berbahagia, terasing dan merasa tak mengenali istrinya lagi. Aku tak ingin terlambat menyadari ini.
Baca juga: Menakar Seribu Berkat
Dunia buku yang sekian waktu terkubur mau tak mau harus kukenalkan pada suamiku. Masa kami punya dunia sendiri-sendiri, masa lalu. Aku ingin ia tahu bahwa aku begitu mencintai buku pada suatu ketika. Aku tak boleh sibuk memikirkan ada apa denganku ini dengan membiarkan Jamal kebingungan sendirian. Aku tertawa.
“Ada apa Love?”
“Aku positif,”.
Jamal terbelalak dengan sorot mata berkilau. Dadaku kembali terisi mendapati air wajah Jamal yang ini. Pancarkan kesungguhan. Lelaki istimewa. Aku tahu dia bukan manusia tanpa idealisme. Aku sudah lama tak merawat idealisme dirinya di diriku.
“Jangan girang dulu, mungkin karena sebuah ciuman dari sang pujangga besar itu,” godaku.
Turen, 2024
(*) Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, Hasta Mitra, Jakarta, 1980.
(Editor: Iman Suwongso)
